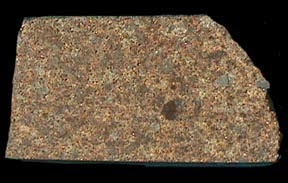Pejabat-pejabat
kompeni dalam abad ke-18 terkenal korup dan serakah. Mereka hanya
memikirkan bagaimana menjadi kaya raya dalam waktu yang sependek
mungkin, dan kemudian kembali ke negeri Belanda atau menetap di Hindia
dengan gaya hidup mewah. Residen-residen di Cirebon yang paling serakah
diantara residen-residen kompeni, dan kedudukan di Cirebon yang paling
didambakan. Batavia hampir-hampir tidak ada kekuasaan sama sekali
terhadap residen-residen Cirebon. Residen-residen itu berusaha untuk
menguasai semua perdagangan dari hampir segala macam hasil rakyat, dan
dengan demikian menyebabkan kemunduran dan hampir memusnahkan golongan
dagang pribumi, dan bahkan hampir melumpuhkan segala aktivitas dagang
pribumi.
Beras, kapas, nila, lada, kayu, gula, kacang-kacangan dan
sebagainya yang dihasilkan oleh rakyat dibeli oleh residen-residen itu
dengan harga serendah mungkin. Hasil padi misalnya, sebanyak 300 koyang
setahun atau 1.350.000 kg dibeli dengan harga sangat rendah, 25 ringgit
satu koyangnya. Tiap produk yang berharga untuk pasaran dikuasai oleh
residen, dan dibayar dengan mata uang yang sudah merosot nilainya.
Desa-desa secara keseluruhan disewakan kepada orang-orang Cina, yang
memungut pajak, menjual candu, dan menguasai tenaga kerja. Untuk menutup
mulut pejabat di Batavia, para residen membagi barang rampasannya
dengan beberapa pejabat di Batavia. Para residen Cirebon bahkan
menyerahkan tenaga kerja rodi ke Batavia sebanyak 200 orang atau lebih
setahun. Kemiskinan dan pemerasan lewat pajak dan cara-cara lain
menimbulkan suatu kejahatan sosial, ialah perbudakan manusia atau
menjual diri dan keluarga ke dalam perbudakan.
Terjadinya
penjualan diri untuk menjadi budak secara besar-besaran menggelisahkan
orang Belanda, dan walaupun tidak sama sekali menutup mata terhadap
kesalahan diri sendiri, namun para Sultan dan pangeran dipersalahkan
atas penderitaan penduduk ini. Sejumlah besar pengikut sultan-sultan dan
keluarga mereka merupakan beban berat bagi kaum tani, terutama dalam
perjalanan-perjalanan mereka ke desa-desa. Dan para pangeran masih
dianggap miskin oleh orang Belanda, yang mengatakan bahwa
pangeran-pangeran ini tidak tinggal dalam istana-istana terbuat dari
batu, melainkan hanya dari kayu saja. Mungkin ini hanya penilaian
Belanda berdasarkan atas pendapat mereka mengenai gaya dan konsepsi
mengenai kemewahan, dan bukan atas kenyataan-kenyataan di Cirebon. Sebab
siapapun yang melihat hasil ukiran kayu dan arsitektur batu Cirebon,
akan mengagumi keindahannya. Diperkirakan bahwa para residen pada abad
ke-18 mendapatkan 60.000 ringgit setahunnya. Yang paling serakah, Graf
van Hogendorp, mendapat 100.000 ringgit tiap tahun. Walaupun demikian,
residen-residen itu mempunyai staf kulit putih yang sangat kecil,
terdiri atas beberapa orang, dan untuk mendapat keuntungan-keuntungan
mereka sangat tergantung kepada bantuan dan kerjasama para bangsawan
pribumi. Sebagai imbalan, mereka mendapatkan segala perlindungan dari
kompeni.
Di tengah-tengah kemajuan kebudayaan istana Cirebon pada
abad ke-18, seperti yang terlihat pada ukiran kayu dan kesenian batik,
dan kemewahan residen-residen Belanda, diantaranya Graf van Hogendorp
yang memelihara 16 orang pemain musik yang harus main pada tiap waktu
makan, rakyat dilanda bencana wabah penyakit dan kelaparan. Tahun-tahun
1719, 1721, 1729, 1756, 1757, 1773, 1775, 1776, 1792, dan 1812 merupakan
tahun-tahun bencana kelaparan dan wabah penyakit bagi rakyat Cirebon.
Suatu laporan dari tahun 1765 mengisahkan bahwa tidak ada perdagangan
antara kaum pribumi, yang telah demikian miskin dan habis kekuatan
mereka karena eksploitasi dan bencana alam. Dalam wabah tahun 1773 dan
1775, di kota Cirebon setiap hari 50 orang meninggal dunia. Menurut
suatu laporan Belanda, dalam tahun 1806 berkurangnya penduduk dan
surutnya kedudukan Sultan, bahkan menyebabkan Sultan-sultan ini tidak
lagi mempunyai pembantu-pembantu. Pelabuhan Cirebon pada akhir abad
ke-18 dan permulaan abad ke-19 menjadi demikian tidak sehatnya, sehingga
residen harus memindahkan markas besarnya ke tempat lain, pemerintahan
Belanda pada umumnya hancur setelah Van Hogendorp yang serakah itu.
Barangkali
pemerintahan Van Hogendorp di Cirebon merupakan yang paling buruk dalam
sejarah daerah itu selama pemerintahan lama kompeni. Waktu Van
Hogendorp pulang ke negri Belanda, kapalnya tenggelam karena terlalu
banyak memuat barang rampasannya dari Hindia Belanda, demikian menurut
gunjingan orang pada waktu itu.
Namun, perubahan-perubahan
sampai juga di Cirebon, Perubahan ini datang karena kejadian-kejadian di
negri Belanda dan Eropa. Pada akhir tahun 1790-an revolusi Prancis
sampai di Negri Belanda, yang menjadi Bataafsche Republiek di bawah
naungan Prancis. Namun Prancis jatuh di bawah hipnose 'Prajurit
Revolusi' dan kaisarnya, Napoleon Bonaparte, yang bermurah hati
mengangkat saudaranya sendiri Louis Bonaparte, menjadi raja Belanda.
Raja mengirim ke Hindia Belanda salah seorang pahlawan dan pemimpin
renolusi belanda, Marsekal H.W. Daendels, seorang pengagum Napoleon,
untuk memperbaiki pemerintahan Kompeni (yang telah berakhir tahun 1799),
yang telah diambil alih oleh pemerintah Belanda. Daendels menganggap
dirinya sebagai Napoleon kecil, yang harus memperbaiki pemerintahan
Kompeni yang korup dengan sistem prokonsulnya atau petualang-petualang
yang memperkaya diri, dan bukan pejabat-pejabat di bawah satu hirarki
birokrasi, seperti yang dikehendaki Napoleon sebagai suatu syarat negara
modern. Walaupun gaji Residen Cirebon pada waktu itu diperkirakan
sebanyak 25.000 ringgit setahun, Daendels menggajinya 17.000 ringgit
setahun, sama dengan residen-residen yang lain.
Di Cirebon sendiri
terjadi semacam revolusi yang lain. Keadaan yang tidak stabil, yang
oleh orang Belanda disebut kejahatan dan kerusuhan, telah mengganggu
Cirebon sepanjang abad ke-18. Gerombolan-gerombolan perampok atau
pemberontak merajalela, sulit untuk membedakan antara politik dan
kejahatan, yang menghancurkan daerah-daerah Cirebon yang agak terpencil.
Pendeknya, ketidaktenteraman selalu terdapat di sana. Pada akhir abad
ke-18 ketidakpuasan dan kejahatan menemukan titik pusat. Pada tahun 1798
seorang Sultan Kanoman, tidak sesuai tradisi lama, telah mendahulukan
putra kesayangannya untuk menaiki tahta melampaui ahli waris yang sah.
Keadaan mungkin masih bisa dikendalikan seandainya ahli waris yang
ditunjuk, Sultan yang baru, tidak menyia-nyiakan kakaknya, yang hidup
dalam kemiskinan. Hal ini menyakitkan hati para bangsawan dan pemuka di
Cirebon. Mereka mengajukan protes terhadap keadaan ini. Bahkan
orang-orang dari Kasepuhan ikut mempersoalkan putra yang telah dicabut
hak warisnya. Jadi, mungkin yang menyebabkan orang-orang berontak bukan
soal sah atau tidak sahnya, melainkan pencabutan hak waris antara semua
kelas yang menimbulkan kemarahan mereka, dan membuat mereka
mengidentifikasikan diri dengan persoalan pangeran yang dicabut
hak-haknya. Pendeknya, pada tahun 1804 para petani Cirebon langsung
menuju ke Batavia, yang mereka anggap sebagai sumber utama dari segala
kejahatan yang menimpa mereka, sedangkan yang menarik perhatian dan
memang tepat sekali, untuk sementara mereka tidak mempedulikan keadaan
di Cirebon. Sayang sekali bagi orang-orang yang memprotes, mereka
dihalau di Karawang. Dalam pada itu, para petani mengusir Cina-cina dari
daerah pedalaman, para pemegang kontrak atas desa mereka. Sebenarnya
kejadian-kejadian tersebut merupakan yang paling hebat dari
pemberontakan-pemberontakan pada permulaan tahun 1800-an, yang terkenal
sebagai 'Pemberontakan-pemberontakan Cirebon'. Pemberontakan berakhir
pada tahun 1819, dan secara kecil-kecilan terjadi lagi pada tahun 1825.
Pada
tahun 1806, dicoba diadakan perjanjian perdamaian antara para
pemberontak dan orang-orang Belanda, yang mengembalikan Pangeran
Kanoman, yang dicabut hak warisnya, dari pembuangannya di Ambon, yang
mendapatkan kedudukan tinggi di Cirebon dan mendapatkan tanah. Belanda
menyanggupi untuk menjauhkan orang-orang Cina dari desa-desa,
menghentikan eksploitasi dan penyalahgunaan yang paling buruk, dan
beberapa janji lainnya. Namun pemberontakan terus berlangsung,
kadang-kadang di bawah pimpinan orang-orang terkenal dan kadang-kadang
diadakan oleh gerombolan-gerombolan tersebar di sana-sini. Perang
Cirebon mencapai titik puncak selama pemerintahan Inggeris pada tahun
1811-1812.
Di samping pemberontak-pemberontak Cirebon, Belanda di
bawah Daendels menghadapi perang lain lagi, ialah perang melawan
Inggeris yang menentang Eropa di bawah Napoleon. Pada tahun 1811
orang-orang Inggeris berhasil mendarat di Jawa dan mengalahkan tentara
Belanda. Banyak pasukan pribumi dalam tentara Belanda bercerai-berai di
pedalaman, dan mulai beroperasi sendiri-sendiri. Di Cirebon seorang
bangsawan, Bagus Rangin berhasil menghimpun gerombolan-gerombolan yang
berkeliaran ini dan memimpin pemberontakan untuk menghalau semua orang
asing dan menghentikan penyalahgunaan. Beliau mungkin pemimpin
pemberontak yang paling besar di Cirebon, dan pada suatu saat dikabarkan
telah menghimpun pasukan pemberontak sebanyak 2000 orang bersenjata
api. Pada tahun 1812 orang-orang Inggeris sedikit banyak berhasil
menundukkan pasukan Bagus Rangin dan membendung gelombang besar
pemberontakan. Tapi pemberontakan masih tetap membara sampai 1819 di
bawah pemimpin yang berbeda-beda dan timbul lagi sebentar pada tahun
1825.
Suatu aspek sejarah Cirebon
yang luar biasa adalah bahwa jikalau permulaan abad ke-19 penuh dengan
pembangkangan heroik melawan ekonomi kolonial yang masuk ke dalam,
sebaliknya pembangkangan ini hilang lenyap selama tahun-tahun berikutnya
dalam abad itu. Tiba-tiba daerah itu menjadi seolah-olah yang paling
damai dari semua distrik di Jawa. Padahal di sini juga tuntutan sistem
tanam paksa dari 1830-1870, yang mempunyai perkebunan-perkebunan negara
kolonial di seluruh Jawa, sangat menekan rakyat dalam bentuk tenaga
kerja dan penggunaan tanah. Dari laporan-laporan dapat diketahui,
bagaimana pemilikan tanah para petani dihancurkan oleh ekonomi
perkebunan.
Mengenai sejarah politik dan pemerintahan Cirebon,
abad ke-19 juga mendatangkan perubahan-perubahan dan penyesuaian dengan
politik dan pemerintahan langsung Negeri Belanda. Pengangkatan kembali
sultan Kanoman pada tahun 1806 tidak berhasil mengakhiri
pemberontakan-pemberontakan. Pada tahun 1809, H.W. Daendels mengakhiri
status khusus dari sultan-sultan dan pangeran-pangeran dari Cirebon
sebagai kekuasaan setengah merdeka. Daendels memutuskan bahwa Cirebon
menjadi suatu propinsi pemerintah (dengan arti Hindia Timur Belanda),
dan para sultan dinyatakan sebagai abdi negara Hindia Timur, dan
kekuasaan politik apa pun yang masih ada pada mereka ditempatkan di
bawah pengawasan Belanda. Perubahan-perubahan yang diadakan oleh
Daendels tidak diperinci lebih lanjut dan tidak berarti banyak, karena
sejak lama para sultan tidak ada keinginan untuk menjalankan kekuasaan
mereka, atau mereka menggunakannya dengan cara lain atau untuk tujuan
lain daripada Belanda. Pendeknya, tidak ada yang menentang atau
kelihatan adanya kesulitan sebagai akibat tindakan Belanda yang
sewenang-wenang itu. Raffles, pejabat Inggris yang menggantikan Gubernur
Jenderal Belanda, melangkah lebih jauh lagi. Ia memberikan kepada para
sultan tanah persawahan bebas pajak yang ditentukan secara jelas, dan
memberikan kepada Sultan Kasepuhan dan Sultan Kanoman suatu subsidi uang
masing-masing sebesar 8000 rupee setahun. Ketika Belanda kembali di
Jawa (1819) setelah Napoleon jatuh, dan setelah perjanjian perdamaian
Kongres Wina, Belanda mengesahkan keadaan yang diciptakan oleh Daendels
dan Raffles. Kedudukan politik para sultan dihapuskan, tetapi tiap
sultan (Kasepuhan dan Kanoman) menerima subsidi uang sebesar 18.000
gulden setahun. Sultan-sultan pertama yang "digaji" wafat pada tahun
1845 dan 1851. Kira-kira 30 tahun kemudian, Cirebon menjadi suatu
residensi 'Hindia Belanda' seperti residensi-residensi lainnya di bawah
pemerintahan langsung Belanda, tetapi pemerintahan langsung ini berarti,
bahwa pejabat-pejabat Belanda, seperti residen dan asisten residen,
pada tingkat distrik semua dibantu oleh kepala-kepala pemerintahan
pribumi (pangreh praja) yang dipimpin oleh seorang bupati. Bupati-bupati
Cirebon pada abad-abad ke-19 dan ke-20 bahkan tidak diambil dari
keluarga sultan, melainkan dari tempat lain, dan jika ada bupati yang
berasal dari keluarga sultan, maka ini hanya kebetulan saja dan tidak
disengaja. Para sultan Cirebon malahan mengundurkan diri ke dalam
istana-istana mereka, dan menjadi pelindung kesenian tradisional
mengukir kayu, membuat wayang dan membatik.
Tidaklah terlampau
aneh bahwa penghapusan kekuasaan politik para sultan memungkinkan mereka
untuk mencurahkan perhatian kepada pengembangan seni dan budaya.
Bukannya kebudayaan istana sendiri, melainkan mendorong kesenian
tradisional di desa-desa dan di antara orang-orang yang tinggal di atas
tanah sultan. Bidang inilah yang mengembalikan sebagian pengaruh dan
prestise keluarga sultan di mata rakyat Cirebon. Menyadari bahwa para
sultan tidak dapat dibebani tanggung jawab atas kesengsaraan yang mereka
derita, maka penduduk di desa-desa barangkali pertama-tama tidak
mengindahkan mereka. Tetapi kemudian, waktu kolonialisme makin menyerbu
ke dalam desa-desa dan masyarakat, orang-orang mulai memihak kepada
sifat-sifat khusus kebudayaan istana Cirebon dan kharisma keagamaan
sultan sebagai keturunan wali keramat, Sunan Gunung Jati. Kemudian,
istana sekali lagi menjadi pusat bagi rakyat. Di Cirebon rupanya tradisi
istana untuk memberi dorongan kepada kesenian di luar tembok istana
telah menciptakan hubungan yang kokoh dengan para petani. Usaha rakyat
untuk menemukan kembali kepribadian mereka selama penetrasi kolonialisme
dan pembaratan memungkinkan terjadinya hubungan ini. Dengan demikian,
apa yang telah dilepaskan oleh para sultan kepada Belanda dalam bentuk
material, telah kembali pada mereka dalam bentuk spiritual.....